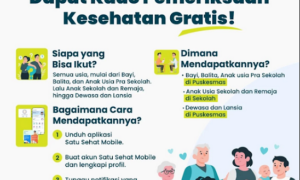Oleh: NANI EFENDI
Judul di atas terinspirasi dari novel karya A.A. Navis, Robohnya Surau Kami. Novel yang terbit pada tahun 1956 ini bukan bercerita tentang benar-benar robohnya sebuah surau, tapi robohnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat. Judul yang senada juga pernah dipakai oleh Karni Ilyas di acara ILC, dalam rangka kritik terhadap kondisi dunia hukum di Indonesia, yang berjudul Robohnya Mahkamah Kita. Saya tergerak untuk membuat tulisan ini setelah mendengar sebuah ceramah Rocky Gerung.
Ketika bertemu mahasiswa, Rocky katanya sering bertanya, “Kapan DO?” Pertanyaan itu ditanggapi
dengan terkejut oleh mahasiswa, “Kok DO?” Kata Rocky, “Ya,
kalau udah tahu mata kuliah isinya bodoh ngapain Anda ikuti. DO aja! Belajar
sendiri aja. Selama otak kita ada, kita bisa belajar.” Cerita itu
disampaikan Rocky pada saat ia menjelaskan bahwa ia pernah membongkar kasus
plagiasi dari seorang pejabat. Pejabat dimaksud pernah jadi rektor, dan ingin
maju lagi menjadi gubernur. Pejabat itu berupaya memperoleh gelar “profesor
doktor” agar bisa menambah nilai jual, mungkin. Tapi diduga disertasinya palsu alias hasil plagiat (jiplak).
Rocky membongkar disertasi itu.
Disertasi tentang ilmu fisika. “Saya baca secara singkat, grammar-nya
kok kacau?” kata Rocky. Ternyata, disertasi itu saduran dari disertasi orang
lain. Disertasi yang aslinya itu ada di Texas, Amerika Serikat. Itu baru diketahui
ketika dicek di internet. Ternyata itu disertasi plagiat (palsu) dengan cara
diterjemahkan melalui aplikasi Google translate. Ia ketahuan, kata Rocky, karena
salah menterjemahkan kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Di situlah ketahuan
bahwa disertasi itu memang palsu. Disertasi karya orang lain yang diterjemahkan
menggunakan Google translate. Maka Rocky menegaskan, “98 persen disertasi di
Indonesia ini palsu. Dari logika palsu.”
Gelar akademis pejabat perlu
diragukan
Dari penjelasan Rocky itu, saya
jadi merenung sendiri: itu sekelas rektor, melakukan plagiat. Apalagi sekelas
mahasiswa S2 atau S1. Terlebih di perguruan-perguruan tinggi kecil. Bahkan, saya dengar ada dosen melakukan “jual-beli” skripsi pada mahasiswa. Mahasiswa membayar sejumlah
uang untuk membuat skripsi. Jadi yang membuat skripsinya dosennya sendiri. Apakah
itu bukan pembodohan yang nyata terhadap mahasiswa? Benar-benar parah
pendidikan formal kita saat ini. Oleh karena itu, saya tak begitu kagum dengan
banyaknya lulusan S2 dan S3 saat ini. Saya tak terlalu pedulikan gelar akademisnya.
Saya lebih kagum dengan seseorang itu dari karyanya. Kalau pun saya kagum pada
doktor, yang saya kagumi bukan gelarnya, melainkan karya-karya tulisnya,
pemikiran-pemikirannya, dan prestasi-prestasi akademis-intelektualnya. Saya
kagum misalnya dengan doktor Nurcholish Madjid, Arief Budiman, Fachry Ali, F. Budi Hardiman,
dan lainnya.
Saya juga terkadang sering heran
dengan banyak pejabat hari ini (bupati, gubernur, anggota dewan), yang punya kesibukan yang cukup padat, tapi
ujug-ujug bisa dapat gelar doktor, gelar profesor, dan gelar mentereng lainnya.
Anehnya juga, masyarakat kagum luar biasa dengan gelar-gelar itu. Maka sering kita
dengar perbincangan di masyarakat: “Dia itu doktor. Pak Bupati Kabupaten X itu
doktor. Gubernur A itu doktor. Kepala dinas itu sudah doktor sekarang.” Bahkan,
ada yang marah-marah kalau gelarnya tidak dipasang pada namanya. Mestinya,
masyarakat itu kritis sedikitlah. Bukankah para pejabat itu super sibuk?
Mestinya, ketika seorang pejabat dapat gelar doktor pada saat ia menjabat, kita
pantas pertanyakan secara kritis: kapan ia kuliah? Kalau ia kuliah, apakah ia
punya waktu untuk mempelajari mata kuliah dengan baik? Dan kapan ia melakukan riset (penelitian)? Bukankah mereka super sibuk?
Jadi, saya, bukannya kagum pada
para pejabat yang ujug-ujug dapat gelar akademis di tengah kesibukannya
menjabat, malah saya meragukannya. Dan memang harus diragukan. Terlebih saat
ini gelar hanya dijadikan pajangan pada nama agar terlihat keren dan disegani.
Padahal, kemampuan intelektual tak ada. Malah tak sedikit sekarang ini gelar
akademis didapat dengan cara tak terpuji. Sudah banyak juga diketahui orang,
untuk dapat gelar magister, doktor, tak perlu susah payah. Kalau ada uang
banyak, gelar bisa diperoleh. Majalah Tempo edisi 1-7
Februari 2021 pernah mengungkap skandal mahasiswa maupun kampus dalam upaya
memperoleh maupun memberikan gelar akademis dengan cara-cara tak terpuji. Tertulis
pada cover Tempo: “Wajah Kusam Kampus”.
Dan, kemampuan sebagian para
dosen sekarang ini pun perlu diragukan juga. Seperti kemampuan dosen
menerbitkan tulisan di jurnal-jurnal internasional, misalnya. Terkadang tak
murni hasil kemampuan mereka. Tapi itu terkadang diakali dengan cara-cara
tertentu. Itu sudah banyak saya dengar dari berbagai sumber. Meski begitu, saya
tak mengatakan semua dosen saat ini seperti itu. Tidak. Dosen yang hebat di
Indonesia sangat banyak. Saya mengatakan, saat ini ada fenomena seperti
itu: fenomena pendangkalan intelektual. Dan itu yang mesti kita kritisi. Masyarakat
mesti kritis terhadap fenomena budaya bangga-bangga dengan gelar akademis,
sibuk urusan sertifikasi dosen (angka kredit), sibuk dengan jabatan akademis, sibuk ngejar
jabatan di instansi-instansi pemerintah, ngejar jabatan politik, dan
sebagainya. Padahal kemampuan akademis dan karya intelektual mereka minim.
Nilailah dari karya
intelektualnya, bukan dari gelarnya
Saya adalah orang yang tak mau
sembarang kagum pada gelar seseorang. Jangankan sekelas gelar magister, gelar
doktor pun saya lihat dulu sejauh mana kemampuan akademis-intelektualnya.
Kemampuannyalah yang saya kagumi, bukan gelarnya. Oleh karena itu, saya banyak
kagum pada tokoh-tokoh hebat meskipun mereka tak punya gelar akademis atau
gelar akademisnya hanya S1. Beberapa contoh misalnya Gus Dur, Pramoedya Ananta
Toer, Goenawan Mohamad, Emha Ainun Nadjib, Sudjiwo Tedjo, Ridwan Saidi, dan lainnya. Di bidang politik dan pemerintahan ada Mar’ie Muhammad, Fahmi Idris, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, dan lainnya. Gus Dur sengaja keluar dari kuliah karena merasa apa yang diajarkan di
kampusnya sudah ia pelajari semua. Tapi walaupun tak punya gelar, Gus Dur
diakui kehebatannya sebagai seorang intelektual, budayawan, kolomnis, dan juga
kiai.
Jadi, kalaupun saya kagum pada
tokoh-tokoh yang bergelar doktor atau profesor, yang membuat saya kagum adalah
kemampuannya, terutama karya-karya tulisnya. Banyak juga para profesor dan doktor
yang saya kagumi misalnya Franz Magnis-Suseno, Sindhunata, F. Budi Hardiman, Ariel
Heryanto, Jalaluddin Rakhmat, Yudi Latif, Ignas Kleden, Refly Harun, dan lainnya. Mereka-mereka ini saya kagumi karena kehebatan
intelektualnya, bukan pada gelar akademisnya semata. Jadi, kampus harus kembali kepada idealisme sebagai lembaga pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan manusia, bukan “dagang gelar”. Dengan begitu, kampus kita bisa tetap “tegak” dan “tak roboh” sebagaimana cerita Robohnya Surau Kami karya A.A. Navis.
NANI EFENDI, Alumnus
HMI